Read more
Hai Sobat Kumpulan Cerpen Siti Arofah Kali ini aku mau menceritakan sebuah kisah seorang anak jalanan yang berjuang untuk bertahan hidup di jalanan Jakarta. Dibalut dengan bahasa yang dramatis, kita akan diajak menjelajahi dunia gelap dan penuh tantangan yang dihadapi oleh anak-anak jalanan di kota ini. Dari konflik dengan geng rival hingga upaya untuk menemukan kedamaian dalam kehidupannya, petualangan anak jalanan ini akan membuatmu terharu dan terinspirasi.
Di tengah keramaian Jakarta, di bawah jembatan layang yang selalu riuh dengan suara klakson kendaraan dan deru mesin, hidup seorang anak jalanan bernama Bimo. Anak laki-laki berusia 12 tahun ini sudah bertahan hidup di jalanan sejak usia tujuh tahun, setelah ia kehilangan keluarganya akibat sebuah tragedi yang bahkan tak pernah ia pahami sepenuhnya. Di balik wajahnya yang polos dan tatapan mata yang tajam, Bimo menyimpan keinginan sederhana yang selama ini ia perjuangkan: kedamaian.
Setiap hari, Bimo mengamen dan terkadang mengemis demi sekadar membeli nasi bungkus. Ketika malam tiba, ia akan tidur di mana saja, bisa di emperan toko yang sudah tutup, atau di kolong jembatan bersama teman-teman anak jalanan lainnya. Hidup di jalanan mengajarkan Bimo untuk selalu waspada. Dunia ini, dunia jalanan, tidak ramah bagi mereka yang lemah.
Suatu malam, ketika Bimo sedang duduk termenung di bawah lampu jalanan yang remang, sahabatnya, Seno, seorang anak jalanan yang lebih tua darinya, datang dengan wajah khawatir.
“Bim, lo harus hati-hati. Tadi gue lihat anak-anak geng Manggarai muter-muter di sekitar sini,” ujar Seno dengan suara berbisik.
Bimo hanya mengangguk, wajahnya tak menunjukkan rasa takut. “Biarkan aja, Sen. Gue udah capek takut sama mereka.”
Seno menghela napas panjang. “Gue ngerti, Bim. Tapi lo tau sendiri kan, anak-anak itu nggak segan-segan buat nyakitin siapa pun yang ngelanggar daerah mereka. Mending kita cabut dari sini dulu,” sarannya sambil melirik sekitar.
Namun, Bimo hanya tersenyum kecil. “Gue udah lelah, Sen. Selalu kabur, selalu sembunyi. Kita kan sama-sama cari makan di jalan, kenapa mereka harus ngusir kita?”
Malam itu, Bimo dan Seno duduk di bangku kayu pinggir jalan, menatap lampu kota yang berpendar. Dalam hati, Bimo merasa ada sesuatu yang kosong. Di balik semua ketegangan dan pertempuran untuk bertahan hidup, ada keinginan sederhana yang ia dambakan: tempat yang tenang, tempat di mana ia bisa tidur tanpa rasa takut, dan sebuah rumah yang bisa ia sebut ‘rumah’.
“Kapan ya, kita bisa hidup tenang kayak orang-orang di gedung-gedung itu?” tanya Bimo sambil menunjuk ke arah gedung tinggi di kejauhan, matanya menerawang.
Seno hanya mengangkat bahu. “Mungkin suatu hari nanti, kalau kita bisa kumpulin uang. Tapi ya… jalanan ini satu-satunya tempat yang kita punya sekarang, Bim. Jangan berharap terlalu banyak, nanti lo kecewa.”
Namun, Bimo tak bisa menghentikan keinginannya untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Dia tahu, selama ia bertahan hidup di jalanan, ia harus menerima kenyataan bahwa setiap hari adalah perjuangan. Meski begitu, ia memutuskan malam itu bahwa ia akan mencari jalan untuk keluar dari kerasnya hidup jalanan ini, bagaimanapun caranya.
Hari-hari berikutnya, Bimo semakin hati-hati. Ia menghindari area-area yang dikuasai geng anak jalanan lainnya dan mencoba mencari pekerjaan kecil-kecilan. Ia mulai membantu pedagang di pasar, meskipun bayarannya hanya sekadar makanan. Setiap receh yang ia dapatkan, ia sisihkan dengan harapan bisa menggunakannya untuk mencari kehidupan yang lebih baik.
Suatu hari, saat ia sedang mengangkat peti sayuran untuk seorang pedagang, seorang pria paruh baya bernama Pak Rahmat memperhatikannya. Pak Rahmat adalah seorang penjaga kios yang sering melihat Bimo di pasar. Rasa iba dan kekaguman pada semangat Bimo membuat Pak Rahmat memberanikan diri untuk mengajak Bimo berbicara.
“Bimo, kamu masih kecil, tapi kerja keras sekali. Apa nggak capek?” tanya Pak Rahmat sambil menyodorkan sebotol air mineral.
Bimo tersenyum kecil, menerima air tersebut. “Iya, Pak. Capek sih, tapi saya harus kerja. Kalau nggak kerja, nggak makan.”
Pak Rahmat terdiam, memandangi Bimo dengan tatapan prihatin. “Kamu nggak punya keluarga, Nak?”
Bimo hanya menggelengkan kepala, menunduk sedih. “Nggak ada, Pak. Saya sendirian.”
Pak Rahmat mengangguk, lalu berpikir sejenak. “Kalau kamu mau, kamu bisa bantu-bantu di kios saya. Nanti saya kasih makan dan sedikit uang. Saya nggak bisa banyak-banyak, tapi semoga bisa bantu kamu.”
Mata Bimo berbinar. Tawaran sederhana itu seperti secercah harapan di tengah hidupnya yang kelam. “Beneran, Pak? Saya bakal kerja keras. Saya janji!”
Sejak saat itu, Bimo mulai membantu Pak Rahmat di kiosnya. Meski hidupnya masih jauh dari kedamaian yang ia idamkan, setidaknya ia merasa punya tempat bernaung sementara. Pak Rahmat bahkan memberikan Bimo selimut tua untuk tidur di lantai kios. Itu sudah lebih dari cukup bagi Bimo yang selama ini hanya beralaskan kardus.
Namun, ketenangan itu tak berlangsung lama. Suatu malam, ketika Bimo sedang membersihkan kios Pak Rahmat, geng Manggarai datang. Mereka melihat Bimo yang kini memiliki “tempat” dan memutuskan bahwa ini adalah penghinaan bagi mereka.
“Hei, Bimo! Gue dengar sekarang lo udah kerja di sini, ya? Hebat!” ejek salah satu anggota geng itu sambil mendekati Bimo dengan tatapan penuh ancaman.
Bimo mencoba untuk tidak terprovokasi. “Gue cuma kerja bantu-bantu, nggak ngerebut apa-apa dari lo semua.”
Tapi anggota geng itu tertawa sinis. “Nggak peduli! Lo tetap di daerah kita. Apa pun yang lo dapet di sini, itu hak kita!”
Situasi semakin tegang, dan Bimo tahu bahwa mereka tidak akan membiarkannya pergi begitu saja. Pada saat itu, Pak Rahmat keluar dari kios dan melihat Bimo sedang dikelilingi anak-anak geng jalanan.
“Hei, kalian mau apa sama Bimo? Dia kerja dengan jujur di sini, jangan ganggu dia!” seru Pak Rahmat dengan tegas.
Anak-anak geng itu tertawa, merasa bahwa Pak Rahmat tak akan bisa melawan mereka. “Pak, ini jalanan, bukan kantor! Siapa aja yang ambil untung di sini, harus bagi sama kita!”
Namun, melihat keberanian Pak Rahmat, Bimo merasa kuat. Ia berdiri tegak, menatap anak-anak geng itu. “Gue nggak akan kasih apa-apa ke kalian. Gue udah cukup capek harus takut terus-terusan. Kalau kalian mau masalah, gue nggak takut!”
Anggota geng itu terdiam, terkejut oleh keberanian Bimo yang selama ini mereka anggap anak lemah. Mereka menggerutu, lalu akhirnya pergi, meninggalkan ancaman di belakang.
Setelah kejadian itu, Pak Rahmat memuji keberanian Bimo, tapi juga menasihatinya. “Bimo, hidup di jalan memang keras. Kadang kita harus belajar untuk bertahan, tapi ingat, jangan pernah kehilangan hati yang baik.”
Kata-kata itu terus terngiang di telinga Bimo. Ia menyadari bahwa perjuangannya bukan hanya untuk mencari kedamaian bagi dirinya sendiri, tapi juga untuk menjaga kejujuran dan kebaikan di tengah dunia yang penuh kekerasan ini.
Berbulan-bulan berlalu, dan Bimo tetap bekerja di kios Pak Rahmat. Meskipun ia masih tinggal di jalanan, Bimo menemukan kedamaian kecil di tengah hidupnya yang sederhana. Setiap hari, ia terus menyimpan harapan bahwa suatu saat ia akan menemukan tempat yang benar-benar bisa ia sebut “rumah.”
Bimo belajar bahwa kedamaian bukanlah sesuatu yang datang tiba-tiba. Kedamaian harus diperjuangkan, bahkan jika itu berarti melawan rasa takut, melawan amarah, dan tetap menjaga hati yang tulus. Meski hidupnya tak sempurna, Bimo akhirnya menemukan bahwa ketenangan bisa hadir dalam kesederhanaan dan ketulusan, dan itulah yang selama ini ia cari.
Seiring waktu, Bimo mulai dikenal oleh para pedagang di pasar. Mereka menghargai ketekunan dan kerendahan hatinya. Ia sering membantu mereka membawa barang dagangan atau sekadar menjaga lapak saat mereka pergi sebentar. Lingkungan pasar ini perlahan menjadi tempat yang terasa seperti rumah bagi Bimo. Para pedagang menganggapnya sebagai bagian dari keluarga besar mereka. Meski sederhana, ia merasa memiliki orang-orang yang peduli padanya.
Suatu sore, ketika Bimo sedang menyapu halaman kios Pak Rahmat, seorang perempuan muda mendekatinya. Perempuan itu mengenakan pakaian sederhana namun rapi, wajahnya tampak penuh belas kasih.
“Hai, kamu Bimo, ya?” sapanya dengan senyum lembut.
Bimo menatapnya ragu. “Iya, Bu. Ada yang bisa saya bantu?”
Perempuan itu mengangguk. “Namaku Bu Laras. Aku bekerja di yayasan yang membantu anak-anak jalanan. Aku dengar tentang kamu dari Pak Rahmat. Kami punya tempat tinggal yang aman, di sana kamu bisa sekolah, dapat makan setiap hari, dan tinggal bersama anak-anak lain yang seumuran kamu.”
Bimo terdiam, terkejut sekaligus bingung. Sekolah dan tempat tinggal yang aman adalah sesuatu yang selalu ia impikan, tapi juga terasa jauh dari kenyataan yang selama ini ia jalani. Setelah berpikir sejenak, ia memandang Bu Laras dengan mata penuh tanya.
“Kenapa saya, Bu? Saya cuma anak jalanan. Saya nggak bisa apa-apa,” ujarnya pelan.
Bu Laras tersenyum, meletakkan tangan di bahu Bimo. “Setiap anak punya hak untuk punya masa depan, Bimo. Kamu mungkin merasa kecil sekarang, tapi di sana, kamu bisa belajar banyak hal dan tumbuh jadi orang yang kuat. Aku hanya menawarkan kesempatan, selebihnya, pilihan ada di tanganmu.”
Bimo menunduk, merasa campur aduk. Di satu sisi, ia ingin menerima tawaran itu, tapi ia merasa meninggalkan kehidupan jalanan sama saja dengan mengkhianati sahabat-sahabatnya yang juga berjuang untuk bertahan.
Malam itu, Bimo merenung, duduk sendiri di tepi jalan, memandang lampu-lampu kota yang menyala di kejauhan. Di tengah keheningan, Seno datang dan duduk di sebelahnya.
“Bim, lo kelihatan galau. Ada apa?” tanya Seno sambil memandang langit.
Bimo menarik napas dalam. “Tadi ada ibu-ibu yang nawarin gue tinggal di yayasan, Sen. Katanya di sana gue bisa sekolah, bisa tinggal di tempat yang aman.”
Seno terdiam sejenak. “Itu bagus, Bim. Lo selalu pengen sekolah, kan?”
“Tapi, Sen… gue nggak mau ninggalin lo semua. Kita udah kayak keluarga di sini,” kata Bimo dengan suara serak.
Seno tersenyum tipis. “Dengerin, Bim. Gue udah lebih tua, hidup gue emang di jalanan. Tapi lo… lo punya kesempatan buat lebih baik. Kalau lo dapet kesempatan buat keluar dari sini, gue dukung penuh.”
Bimo menatap sahabatnya, matanya berkaca-kaca. “Serius, Sen? Lo nggak marah kalau gue pergi?”
Seno mengangguk, lalu menepuk bahu Bimo dengan lembut. “Pergilah, Bim. Cari kehidupan yang lebih baik. Kita semua di sini bakal selalu dukung lo, walaupun mungkin kita nggak ketemu lagi. Lagian, hidup lo di jalanan terlalu keras buat anak kayak lo.”
Keesokan harinya, dengan hati yang berat namun tekad yang kuat, Bimo menemui Bu Laras di yayasan dan memutuskan untuk ikut ke sana. Ia berpamitan pada Pak Rahmat, yang memberinya pelukan hangat dan menitipkan sebuah amplop kecil berisi uang seadanya sebagai bekal.
Saat ia menaiki mobil yang akan membawanya ke tempat baru, ia melihat sahabat-sahabat jalanannya melambai dari kejauhan. Seno tersenyum sambil mengangkat jempol, memberi isyarat dukungan untuk sahabat kecilnya itu.
Di yayasan, Bimo mulai menjalani kehidupan yang benar-benar berbeda. Ia kembali ke bangku sekolah, belajar menulis dan berhitung, belajar bahasa, dan mengenal banyak teman baru. Meski pada awalnya ia merasa asing, lambat laun ia mulai menyesuaikan diri dan merasakan kebahagiaan sederhana dalam belajar.
Tahun demi tahun berlalu. Bimo tumbuh menjadi remaja yang cerdas dan penuh semangat. Ia berhasil menyelesaikan sekolah dasar, lalu melanjutkan ke sekolah menengah dengan tekad yang tak pernah padam. Ia tahu bahwa segala perjuangannya adalah berkat dukungan orang-orang di masa lalu yang peduli padanya.
Suatu hari, setelah sekian lama, ia kembali ke Jakarta, kembali ke pasar yang dulu ia tinggali. Ia mencari Pak Rahmat dan teman-teman lamanya, berharap bisa mengucapkan terima kasih kepada mereka yang telah memberikan awal yang baik baginya. Namun, ia mendapati bahwa banyak hal sudah berubah. Pak Rahmat telah pensiun dan kembali ke kampung halamannya. Seno dan teman-teman jalanannya sudah berpencar, masing-masing menjalani hidup mereka sendiri.
Di tengah hiruk-pikuk kota yang tak pernah berhenti, Bimo berdiri dengan hati penuh rasa syukur. Meskipun kini ia seorang diri, ia tahu bahwa ia tak pernah benar-benar sendiri. Kedamaian yang selama ini ia cari telah ia temukan, bukan pada tempat atau barang, tapi dalam kenangan dan rasa terima kasih pada orang-orang yang pernah hadir dalam hidupnya.
Ia menatap langit, seakan berbicara kepada mereka yang dulu membantunya. “Terima kasih, Pak Rahmat. Terima kasih, Seno. Kalian nggak pernah tahu betapa berharganya kalian buat gue.”
Dengan langkah ringan, Bimo melangkah pergi, membawa harapan baru dan kedamaian yang selama ini ia perjuangkan. Demikian Kumpulan Cerpen Siti Arofah kali ini semoga berkenan di hati.

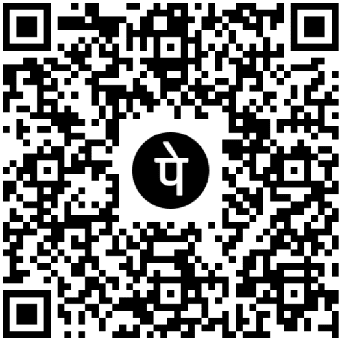








0 Reviews
Terima kasih untuk sobat-sobat yang mau berbagi sharing disini ....